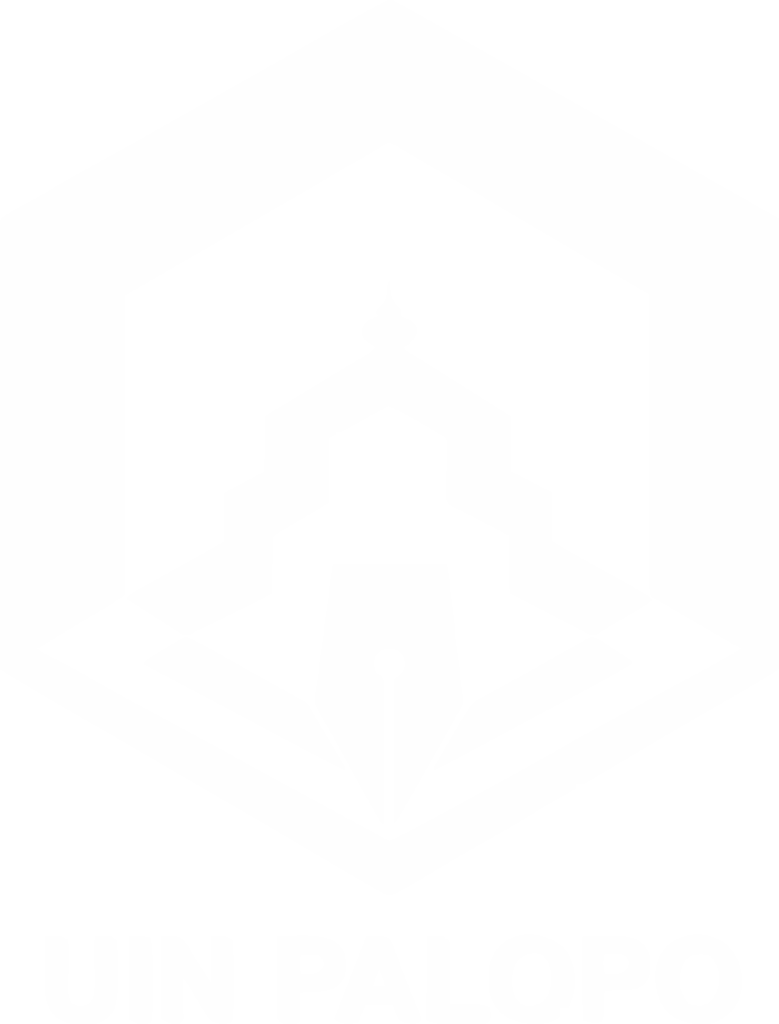Ada masa dalam hidup ketika langkah terasa begitu berat. Jalanan yang kulalui sepi, bahkan terlalu sunyi, hingga suara hatiku sendiri terdengar seperti gema di ruang kosong. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak sorai, hanya ada diriku dan pertanyaan-pertanyaan yang terus berulang:
“Mampukah aku melewati ini? Ke mana arah semua ini membawaku?”
Perjalanan sunyi itu bukanlah pilihan, melainkan keadaan. Aku harus kehilangan banyak hal—orang-orang yang pernah kuanggap tempat bersandar, mimpi-mimpi yang dulu kupeluk erat, bahkan sebagian diriku yang lama. Semua runtuh perlahan, meninggalkan luka yang tak kasat mata. Luka yang hanya bisa kurasakan sendiri dalam diam.
Namun, justru dalam kesunyian itulah aku mulai belajar mendengar. Aku mendengar detak jantungku yang masih berjuang, meski aku hampir menyerah. Aku mendengar bisikan kecil dalam doa, yang sebelumnya tak pernah benar-benar kupahami. Dan aku mendengar tangisanku sendiri yang ternyata mampu membersihkan luka hati.
Hari-hari itu panjang. Setiap langkah seperti seribu kilo. Namun aku terus berjalan, meski tertatih. Aku belajar bahwa perjalanan sunyi bukan berarti perjalanan tanpa tujuan. Justru di situlah aku diajarkan tentang kesabaran, tentang ikhlas, tentang keberanian untuk tetap melangkah meski tanpa kepastian.
Hingga suatu ketika, dari kejauhan, aku melihat seberkas cahaya. Kecil, samar, nyaris tak terlihat. Tapi cukup untuk memberiku harapan. Aku pun melangkah lebih mantap, menembus gelap, menahan perih, hanya untuk mendekat pada cahaya itu. Dan semakin aku berusaha, semakin terang ia terlihat.
Kini aku mengerti, perjalanan sunyi bukanlah hukuman. Ia adalah jalan pendewasaan. Sunyi membuatku berkenalan dengan diriku sendiri, membuatku sadar bahwa cahaya sejati bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam hati yang tak pernah berhenti berharap.
Perjalanan ini memang sunyi, tapi di ujungnya selalu ada cahaya. Dan siapa pun yang berani melewatinya, akan lahir kembali—lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi dunia.