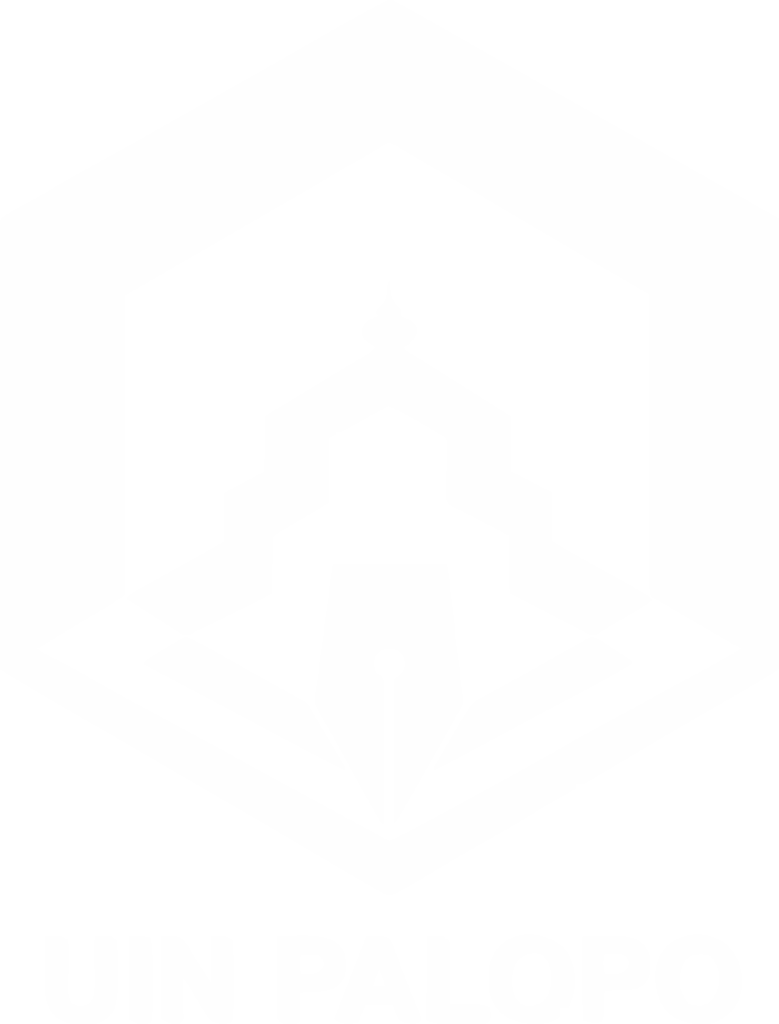Hujan bulan Agustus itu turun seperti tak ada jeda. Jalanan licin, udara dingin menusuk tulang. Dika, mahasiswa tingkat akhir di sebuah kota kecil, berjalan pulang dari kampus sambil memeluk erat map berisi draft skripsinya. Jaket tipisnya basah, tapi ia terbiasa dengan cuaca seperti ini.
Di tikungan dekat pasar, matanya menangkap sosok yang sudah tak asing baginya. Seorang nenek tua duduk di bangku plastik reyot di bawah tenda biru yang bocor di sana-sini. Di depannya ada kotak berisi pisang goreng yang sudah dingin. Nenek itu menggigil, jas hujan plastiknya sobek di bagian bahu. Beberapa orang berjalan cepat melewatinya, bahkan ada yang sengaja menoleh ke arah lain, seolah tak mau melihat.
Dika melambatkan langkah. Dalam hati ia bergulat — uang di dompetnya tinggal cukup untuk makan malam dan ongkos kuliah besok. Jika ia membelanjakan uangnya sekarang, berarti ia harus menghemat dengan mie instan sampai akhir minggu. Tapi tatapan nenek itu… kosong namun lelah, seperti seseorang yang sudah menunggu terlalu lama.
Dika menghela napas, lalu mendekat.
“Berapa semuanya, Nek?” tanyanya sambil menunjuk pisang goreng di kotak itu.
Nenek itu terkejut, matanya sedikit berbinar. “Nak, semua ini? Banyak loh…”
“Semuanya, Nek. Saya beli. Nenek pulang saja, nanti kedinginan.”
Ia menyerahkan uang tanpa menawar, lalu membantu nenek itu membereskan dagangan. Sisa pisang goreng ia bawa, sebagian dimakannya di jalan, sebagian lagi ia bagikan ke anak-anak yang bermain di gang dekat kosnya.
Sejak hari itu, setiap melewati lapak nenek itu, Dika selalu menyapa. Kadang ia membeli satu atau dua pisang, kadang hanya sekadar menanyakan kabar. Suatu pagi, ia datang membawa teh hangat di dalam termos kecil. “Biar badan hangat, Nek,” katanya. Nenek itu tersenyum lebar, senyum yang selalu membuat hati Dika hangat di tengah kesibukannya.
Beberapa bulan berlalu. Hujan kembali datang, kali ini lebih deras dari biasanya. Dika berjalan ke arah pasar seperti biasa, tapi lapak itu kosong. Tidak ada tenda biru, tidak ada aroma gorengan, dan tidak ada nenek yang duduk sambil menunggu pembeli.
Hari berganti, minggu berlalu, lapak itu tetap sepi. Hingga suatu sore, Dika pulang dari kampus dan menemukan sebuah amplop lusuh terselip di bawah pintu kosnya. Namanya tertulis dengan huruf tangan yang gemetar. Dengan hati-hati ia membuka dan membaca:
“Nak Dika,
Jika surat ini sampai padamu, artinya aku sudah tak lagi berjualan. Terima kasih karena selalu menyapaku, membantuku, dan membuatku merasa masih berarti di dunia ini. Aku tak punya banyak untuk membalas, hanya doa agar hidupmu selalu diberkahi.
Jangan berhenti jadi baik, Nak, meski kadang dunia tak membalas. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu.
– Nenek Siti.”
Tangan Dika bergetar. Surat itu hanya satu lembar, tapi terasa berat di hatinya. Ia duduk di lantai, membiarkan air matanya jatuh begitu saja. Ia menyadari bahwa kebaikan sekecil apa pun bisa meninggalkan bekas yang dalam, bahkan ketika kita merasa itu hanyalah hal sepele.
Sejak hari itu, Dika menyimpan surat nenek Siti di meja belajarnya. Setiap kali ia merasa lelah, kecewa, atau bertanya-tanya apakah kebaikan itu masih ada gunanya di dunia yang keras ini, ia membaca kembali surat itu.
Dan setiap kali hujan turun, ia selalu teringat pada tenda biru bocor di tepi jalan, pada senyum hangat seorang nenek, dan pada pesan terakhir yang tak akan pernah ia lupakan:
“Jangan berhenti jadi baik.”
#Jalur3UINPalopo