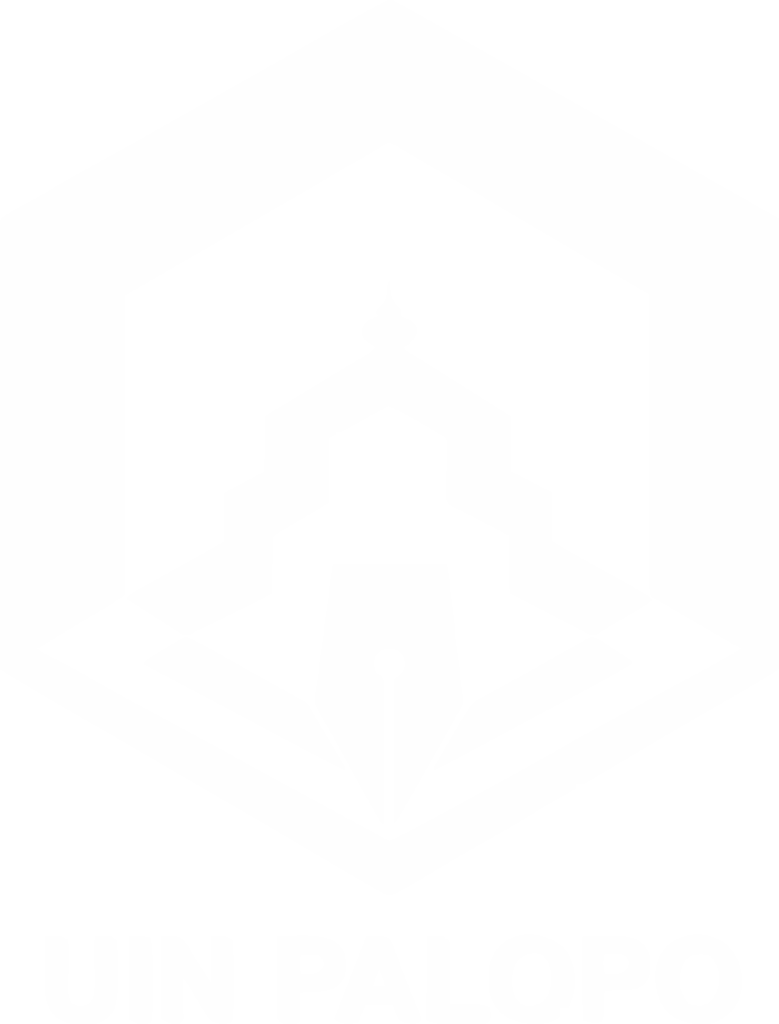Arman tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Hidupnya tidak pernah mudah. Ayahnya seorang sopir angkot yang sering pulang larut malam dengan penghasilan yang pas-pasan. Ibunya berjualan kue di pasar, berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat orang-orang sudah beristirahat.
Sejak kecil, Arman sudah tahu arti kekurangan. Ia pernah berjalan kaki ke sekolah karena tidak punya ongkos, pernah menahan lapar karena uang jajan habis, bahkan pernah menunda bayar SPP karena orang tuanya belum punya cukup uang. Namun, di balik semua kesulitan itu, ada tawa tulus dari orang tuanya, ada kebersamaan dengan teman-teman di gang rumah, ada rasa syukur yang sederhana.
Di benak Arman kecil, terpatri satu hal: “Kalau nanti aku punya banyak uang, aku pasti akan bahagia. Aku tidak mau hidup susah lagi.”
Arman belajar dengan tekun. Ia mendapat beasiswa kuliah, lalu diterima di perusahaan besar setelah lulus. Kariernya melesat cepat. Dari seorang staf biasa, ia menjadi manajer dalam waktu beberapa tahun. Gaji dan bonusnya pun naik berlipat ganda.
Impian masa kecilnya mulai terwujud. Ia bisa membeli motor baru, lalu mobil. Ia membelikan rumah baru untuk orang tuanya, bahkan menyekolahkan adiknya tanpa harus memikirkan biaya.
“Sekarang hidupku sempurna,” pikir Arman.
Namun, lambat laun, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula tuntutan pekerjaan. Ia sering pulang larut malam, bahkan bekerja di akhir pekan. Telepon genggamnya selalu berdering, email masuk tanpa henti.
Arman bisa membeli apapun yang ia mau, tapi ia jarang punya waktu untuk menikmatinya. Mobil mewahnya lebih sering terparkir di garasi. Apartemen mewahnya sepi, karena ia lebih sering tidur di kantor. Bahkan, ia mulai kehilangan momen-momen berharga bersama keluarganya.
Suatu malam, setelah pulang dari kantor yang melelahkan, Arman melihat ibunya duduk di ruang tamu rumah lama mereka. Rumah sederhana itu masih ditempati oleh orang tuanya meskipun ia sudah membelikan rumah baru.
Dengan wajah penuh senyum, ibunya menyodorkan sepiring gorengan hangat. Mereka mengobrol singkat. Di sela-sela obrolan, ibunya berkata:
“Man, ibu bahagia sekali bisa duduk bersama kamu seperti ini. Nggak usah bawa apa-apa, cukup kamu pulang, ngobrol sebentar, itu sudah bikin ibu senang.”
Arman terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya. Selama ini, ia sibuk mengejar materi dengan alasan untuk membahagiakan orang tua. Tapi ternyata, yang paling dibutuhkan orang tuanya bukanlah rumah besar atau uang banyak, melainkan kebersamaan.
Sejak malam itu, Arman mulai sering merenung. Ia teringat teman-temannya di masa kecil yang meskipun hidup sederhana, tetap bisa tertawa lepas, bermain tanpa beban, dan merasa cukup dengan apa yang ada.
“Apakah aku benar-benar bahagia dengan semua ini?” tanyanya pada diri sendiri
Arman akhirnya memutuskan untuk menyeimbangkan hidupnya. Ia tetap bekerja, tapi tidak lagi membiarkan pekerjaannya mencuri seluruh waktunya. Ia belajar berkata “tidak” pada beberapa proyek tambahan, dan memilih menggunakan waktu itu untuk orang-orang yang ia cintai.
Ia mulai rutin makan malam bersama keluarganya, mengajak orang tuanya berlibur, dan meluangkan waktu untuk sahabat lama. Uang yang ia punya ia gunakan bukan sekadar untuk membeli barang, tapi untuk menciptakan pengalaman dan kenangan.
Tak hanya itu, Arman juga mulai berbagi dengan orang lain. Ia menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu anak-anak kurang mampu di kampungnya. Saat melihat senyum mereka, ia merasakan kebahagiaan yang jauh lebih tulus dibandingkan saat membeli barang-barang mewah untuk dirinya sendiri.
Dari perjalanan hidupnya, Arman menyadari satu hal penting: uang memang penting, tetapi bukan segalanya.
-
Uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli ketenangan hati.
-
Uang bisa membeli ranjang empuk, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak.
-
Uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan.
-
Uang bisa membeli rumah mewah, tapi tidak bisa membeli kehangatan keluarga di dalamnya.
Yang benar-benar membawa kebahagiaan adalah hubungan yang tulus, rasa syukur, dan makna hidup.
Kini, Arman tidak lagi bertanya apakah uang bisa membeli kebahagiaan. Ia sudah menemukan jawabannya sendiri: uang hanyalah alat. Bahagia adalah pilihan.